BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai agama yang terakhir diturunkan, Islam merupakan penyempurna agama-agama sebelumnya. Sebagai penyempurna, tentu saja terdapat beberapa ajaran Islam yang sebenarnya telah ada pada agama-agama lainnya. Namun demikian, di waktu bersamaan, Islam juga meluruskan beberapa ajaran agama samawi sebelumnya yang diselewengkan oleh para pemeluknya. Inilah kiranya yang mendorong banyak orang untuk mengkaji dan meneliti Islam lebih dalam lagi, tak terkecuali adalah orang-orang non muslim yang lebih dikenal sebagai orientalist.
Namun Islam sering dipahami secara tidak objektif oleh para orientalist. Dari sini kalangan ilmuwan, peneliti-peneliti agama telah melakukan upaya pendekatan terhadap fenomena agama yang dianggap cukup strategis ketika sebuah ajaran agama ingin dicari nilai-nilai kebenarannya. Tradisi-tradisi keberagamaan yang bisa jadi selama ini hanya sebatas fenomena ritualitas pemeluknya tanpa mengetahui apa makna dan maksud yang tersembunyi dari perintah maupun larangan Allah SWT. Maka Islam perlu dipahami secara fenomenologis dalam menangkap pesan yang disampaikan dalam Al-Qur’an maupun As-sunnah. Fenomenologi adalah suatu bentuk pendekatan keilmuan yang berusaha mencari hakekat dari apa yang ada di balik segala macam bentuk manifestasi agama dalam kehidupan manusia di bumi.
Pendekatan agama secara fenomenologis dalam mengkaji Islam melalui pemaknaan ayat-ayat (tanda-tanda) dari Allah terhadap obyek yang bersifat abstrak maupun hal-hal yang bersifat konkrit . Hal ini dimaksudkan supaya Islam itu benar-benar dipahami dan dimengerti sesuai dengan sudut pandang kebenarannya menurut penganutnya sendiri secara hakiki.
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian fenomenologi?
2. Apa tujuan pendekatan fenomenologi?
3. Bagaimana langkah-langkah pendekatan fenomenologi?
4. Bagaimana problematika pendekatan fenomenologis dalam studi islam ?
5. Bagaimana contoh fenomeologi?
BAB II
PEMBAHASAN
PEMBAHASAN
A. Pengertian Fenomenologi
Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, phenomenon, yaitu sesuatu yang tampak, yang terlihat karena berkecakupan. Dalam bahasa indonesia biasa dipakai istilah gejala. Secara istilah, fenomenologi adalah ilmu pengetahuan (logos) tentang apa yang tampak. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau segala sesuatu yang tampak atau yang menampakkan diri. Seorang Fenomenolog suka melihat gejala Fenomenolog bergerak di bidang yang pasti. Hal yang menampakkan dirinya dilukiskan tanpa meninggalkan bidang evidensi yang langsung. Fenomenologi adalah suatu metode pemikiran, “a way of looking at things”.[1]
Istilah fenomenologi telah lama digunakan, sejak Lambert yang sezaman dengan Kant, juga Hegel, sampai Peirce, dengan arti yang berbeda-beda. Pada era Lambert fenomenologi diartikan sebagai ilusi atas pengalaman. Kata “fenomena” dalam bahasa Inggris disebut phenomena atau phenomenon secara etimologis berarti perwujudan, kejadian, atau gejala. Akan tetapi, pada medio abad XIX arti fenomenologi menjadi sinonim dengan fakta. Pertama kali pada tahun 1764 ia menggunakan istilah ini untuk merujuk pada hakikat ilusif pengalaman manusia dalam upaya untuk mengembangkan suatu teori pengetahuan yang membedakan kebenaran dari kesalahan.
Akan tetapi mayoritas fenomenolog lebih cenderung mengatakan bahwa tokoh yang pertama kali menganggap fenomenologi sebagai sebuah wacana yang bersumber dari filsafat ilmu adalah Edmund Husserl (1859-1938). Karyanya yang berjudul Logische Unteruschungen (1900-1901) untuk pertama kali memuat rencana fenomenologi. Karyanya yang lain adalah Ideen zu einer reinen Phanomenologie und Phanmenologischen Philosophie (1913) dan Farmale und Transendentals Logic (1929). Di dalam buku tersebut ia mengatakan bahwa seorang fenomenolog harus secara sangat cermat “menempatkan fenomenologi harus secara sangat cermat” menempatkan di antara tanda kurung, kenyatan berupa dunia luar. Mulai tahun 1970-an fenomenologi mulai banyak digunakan oleh berbagai disiplin ilmu sebagai pendekatan metologik, dan mengundang kegiatan menerjemahkan karya-karya Husserl. Sejak tahun 1970 hingga sekarang, baik karya-karya Husserl. Sejak tahun 1970 hingga sekarang, baik karya-karya utamanya maupun artikel-artikel yang ditulis banyak diterjemahkan orang, dan tetap menjadi acuan utama pendekatan fenomenologi.
Lebih lanjut metode fenomenologi dikembangkan oleh Rudolp Otto, W. Brede Kristensen, Geradus van der Leeuw, dan Mircea Eliade, juga ditunjukkan gejala itu memberikan interprestasi terhadap gejala itu sehingga maknanya yang tadi tersembunyi dapat pula dipahami.
Pendekatan fenomenologis mula-mula merupakan upaya membangun suatu metodologi yang koheren bagi studi agama. Lebih lanjut Erricker menyatakan bahwa filsafat Hegel dapat menjadi dasar dibangunnya pendekatan ini. Dalam karyanya yang berpengaruh sebagaimana oleh Erricker- The Phenomenology of Spirit (1806). Hegel mengembangkan tesis bahwa esensi (wesen) dipahami melalui penyelidikan atas penampakan dan manifestasi (erschinungen). Tujuan Hegel adalah menunjukkan bagaimana karya ini membawa pada pemahaman bahwa seluruh fenomena dalam berbagai keragamannya, bagaimanapun juga didasarkan pda satu ensensi atau kesatuan dasar (geist atau spirit). Penekanan terhadap hubungan antaraesensi dan manifestasi ini menjadi suatu dasar untuk memahami bagaimana agama dalam keragamannya pada dasarnya mesti dipahami sebagai suatu entitas yang berbeda.[2]
B. Tujuan Pendekatan Fenomenologi
Pendekatan fenomenologi memahami makna atau hakikat yang sebenarnya dari suatu gejala objek yang dikaji melalui jiwa atau kesadaran objek itu sendiri. Dalam arti bahwa pendekatan fenomenologi yang dikembangkan dari pendekatan fenomenologis, membiarkan gejala yang diteliti berbicara sendiri secara tulus dan apa adanya, tidak boleh ada upaya-upaya luar dari sang peniliti membuat prakonsepsi yang macam-macam, apalagi berlebih-lebihan. Berbeda dengan pendekatan ilmiah positivistik, pendekatan fenomenologi dapat memahami adanya keterkaitan objek dengan nilai-nilai tertentu, misalnya keadilan, kemanusiaan, dll.
Sejak zaman Edmund Husserl, arti fenomenologi telah menjadi filsafat dan menjadi metodologi berpikir. Sebagai sebuah aliran filsafat, Edmund Hussrel dianggap sebagai pendirinya. Dalam konteks studi agama, pendekatan fenomenologi tidak bermaksud untuk memperbandingkan agama-agama sebagai satuan-satuan besar, melainkan menarik fakta dan fenomena yang sama yang dijumpai dalam agama yang berlainan, mengumpulkan dan mempelajarinya per kelompok.
Pada intinya ada tiga tugas yang harus dipikul oleh fenomenologi agama, yatu: pertama, mencari hakikat ketuhanan. Kedua, menjelaskan teori wahyu. Dan ketiga, meneliti tingkah laku keagamaan. Pendekatan Fenomenologi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan beberapa hal. Pertama deskripsi tentang berbagai bentuk ekspresi keagamaan yang bersifat tat-upacara, simbolik, atau mistik, disamping deskripsi tentang ajaran-ajaran agam. Kedua deskripsi tentang hakikat kegiatan keagamaan, khususnya dalam hubungannya dalam bentuk ekspresi kebudayaan. Ketiga deskripsi tentang perilaku keagamaan, berupa deskripsi ontologis, deskripsi psikologis dan deskripsi dialektik.
Perkembangan studi agama dengan pendekatan fenomenologis dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Ake Hultzkrantz paling tidak menetapkan tiga poin siginifikansi fenomenologi dalam studi agama:
1. Mencari bentuk-bentuk dan struktur agama-agama, dan akhirnya dari suatu agama tertentu. Para fenomenolog berusaha untuk mengidentifikasi komponen-komponen utama dalam bahan-bahan, struktur, (yang mungkin nampak sebagai fenomena yang independen atau sebagai hubungan antarfenomena) dan fungsi fenomena keagamaan.
2. Berusaha memahami fenomena keagamaan yang bekerja dalam dua tingkatan, pertama, ia mencoba mencari tempat dari sifat bawaan keagamaan dalam suatu budaya, yaitu apa makna agama bagi orang-orang yang ada di dalam kebudayaan tersebut, kedua, ia melibatkan pemahaman umum terhadap elemen-elemen keagamaan dalam hubungan yang lebih luas, yaitu makna teoritisnya.
3. Menyediakan suatu makna bagi sejarah agama-agama dengan cara menerangkannya bersama dan mengintegrasikannya. Fenomenologi agama menawarkan jalan keluar dari dilemma yang memberikan sebuah perspektif bersama bagi semua sejarawan agama, dan memberikan suatu kerangka kerja bagi riset baru yang menggusur gaya lama, sejarah agama yang berorientasi filologi, berupa studi terhadap situasi kegamaan masa kini, akulturasi keagamaan, dan kemunculan bentuk-bentuk keagamaan baru. Dengan demikian hanya dengan bantuan fenomenologi sejarah agama-agama dapat menjadi sebuah disiplin yang mampu menjangkau semua agama.
Meskipun pendekatan fenomenologi agama cenderung muncul belakangan dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan yang lain, seperti sosiologi agama, antropologi agama, psikologi agama, sejarah agama, dan lain-lain, akan tetapi ia memainkan peranan yang sangat penting dalam hal mengungkap makna perilaku keberagamaan manusia dan substansi dari agama-agama itu sendiri.
Maksudnya sebuah fenomena keagamaan cuma bisa diketahui, bila ia dikaji sebagaimana ia muncul menjelma. Dalam suatu ekspresi keagaman, hal inilah yang harus dilakukan. Berupaya mengungkap esensi (wessen) di balik fenomena atau manifestasi (erschinungen). Maka fenomenologi agama adalah metode yang tepat untuk bidang ini, karena metode yang lain niscaya mengabaikan suatu element yang unik yang tidak bisa direduksi di dalamnya
Pendekatan dan pemahaman terhadap fenomena keberagamaan manusia lewat pintu masuk antropologi adalah seperti halnya kita mendekati dan memahami “object” agama dari sudut pengamatan yang berbeda. Dari situ akan muncul pemahaman sosiologis, historis, psikologis terhadap fenomena keberagamaan manusia. Namun diakui bahwa berbagai pendekatan tersebut tidak menyentuh esensi religiositas manusia itu sendiri. Para teolog khususnya kurang tertarik ketika menerima uraian atau masukan-masukan yang disumbangkan oleh pendekatan antropologis terhadap agama.
Dengan demikian, kerjasama antara pendekatan antropologis, sosiologis, psikologis dan historis dengan pendekatan fenomenologis adalah saling melengkapi sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh tentang keberagamaan manusia pada umumnya tanpa sedikitpun mengurangi apresiasi terhadap bentuk keimanan dan penghayatan keberagaman manusia. Kecenderungan beralihnya para teolog dan agamawan dari berbagai kalangan kepada fenomenologi agama tentunya tidak terlepas dari ketidakpuasan mereka terhadap hasil-hasil penelitian agama dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Dengan ungkapan lain bahwa pendekatan tersebut hanya melihat kulit luar keberagamaan manusia saja tanpa memasuki sisi internalitasnya. Pusat perhatian fenomenologi agama sebenarnya hanya terfokus kepada pencarian esensi, makna dan struktur fundamental dari pengalaman keberagamaan manusia. Di dalam pengalaman keberagamaan manusia tersebut terdapat esensi yang irridecible yang merupakan struktur fundamental keberagamaan manusia. Diakui bahwa keberagamaan manusia tidak akan dapat dilepaskan dari sesuatu yang suci. Itulah diantaranya yang merupakan struktur fundamental dan dianggap penting oleh pendekatan fenomenologi ketika menatap realitas keberagaman manusia. Dalam arti bahwa dalam setiap struktur fundamental pengalaman keberagamaan manusia terdapat hal-hal atau sifat-sifat dasar tersebut.
C. Langkah-langkah Metode Fenomenologi
Ada beberapa langkah atau tahapan pendekatan fenomenologi dalam studi agama yang ditawarkan oleh Geradus Van der Leeuw dalam bukunya “Religion in essence and manifestation:A study in phenomenology of religion”:[3]
1. Mengklasifikasikan fenomena keagamaam dalam kategorinya masing-masing seperti kurban, sakramen, tempat-tempat suci, waktu suci, kata-kata atau tulisan suci, festival dan mitos. Hal ini dilakukan untuk dapat memahami nilai dari masing-masing fenomena.
2. Melakukan interpolasi dalam kehidupan pribadi peneliti, dalam arti seorang peneliti dituntut untuk ikut membaur dan berpartisipasi dalam sebuah keberagamaan yang diteliti untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman dalam dirinya sendiri.
3. Melakukan “epochè” atau menunda penilaian (meminjam istilah Husserl) dengan cara pandang yang netral.
4. Mencari hubungan struktural dari informasi yang dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang berbagai aspek terdalam suatu agama.
Tahapan-tahapan tersebut menurut Van der Leeuw secara alami akan menghasilkan pemahaman yang asli berdasarkan “realitas” atau manifestasi dari sebuah wahyu. Fenomenologi tidak berdiri sendiri (operate in isolation) akan tetapi berhubungan dengan pendekatan-pendekatan yang lain untuk tetap menjaga objektivitas.
D. Problematika Pendekatan Fenomenologis dalam Studi Islam
Kesulitan pertama yang dihadapi dalam upaya membangun suatu pendekatan metodologis alternatif yang berakar pada ontologi Islami terletak pada penyingkiran wahyu Tuhan dari wilayah ilmu. Benar bahwa penyingkiran ini memiliki asal-usul dalam batasan tradisi ilmiah Barat sebagai akibat dari konflik internal antara ke agamaan Barat dengan komunitas ilmiah. Juga benar bahwa dalam tradisi Islam, wahyu dan ilmu tidak pernah dipahami sebagai dua hal yang eksklusif. Namun seorang sarjana muslim hampir tidak pernah dapat mengabaikan fakta bahwa wahyu ketuhanan berada di luar aktivitas ilmiah modern.
Serangan gencar terhadap wahyu, yang membawa penyingkiran-nya dari upaya ilmiah Barat, terjadi melalui dua fase. Wahyu disamakan dengan metafisika yang tidak memiliki landasan dan menetapkannya sebagai suatu rival pengetahuan, dipertentangkan dengan pengetahuan yang dianggap benar oleh akal.[4]
Penyingkiran Barat modern terhadap wahyu dari wilayah ilmu tidak didasarkan pada penolakan atas kenyataan bahwa wahyu Tuhan membuat pernyataan yang tidak jelas tentang watak realitas. Penyingkiran itu lebih didasarkan pada pernyataan bahwa hanya realitas empiris yang dapat dipahami. Karena realitas non-empiris (metafisis) tidak dapat diverifikasi melalui pengalaman, maka ia tidak dapat dimasukkan ke dalam wilayah ilmu.
Maka ditegaskan menurut Kant bahwa aktivitas ilmiah mesti dibatasi pada realitas empiris, karena akal manusia tidak dapat menentukan realitas absolut. Argumen di atas adalah argumen yang sederhana dan keliru, karena ia mengabaikan dan mengaburkan sifat dari bukti wahyu dan bukti empiris .Pertama, pengetahuan tentang realitas empiris tidak didasarkan pada pengetahuan yang dipahami secara langsung dan empiris dari lingkungan, tetapi pada teori-teori yang mendeskripsikan struktur dasar realita. Struktur itu tidak segera dapat dipahami oleh indera. Di samping itu, struktur eksistens empiris diinferensiasikan melalui penggunaan kategori-kategori yang diabstraksikan dari hal yan terindera, dan dimediasikan melalui kategori-kategori dan pernyataan-pernyataan rasional murni.
Dengan menggunakan terminologi Lock, kita dapat mengatakan bahwa teori-teori yang kita gunakan untuk mendeskripsikan realitas empiris terdiri dari proposisi-proposisi kompleks yang diperoleh dengan mengkombinasikan sejumlah proposisi-proposisi sederhana. Oleh karena itu pemahaman kita tentang hubungan antara bumi dan matahari dimediasikan oleh konstruk mental, dan oleh karenanya sama sekali berbeda dari kesan singkat yang dipahami oleh indera. [5]
Kedua, argumen di atas gagal melihat bahwa wahyu (paling tidak dalam bentuk final dan islami) mencari justifikasinya di dalam realitas empiris. Dari sudut pandang wahyu Tuhan, realitas empiris adalah manifestasi realitas transendental, dan oleh karenanya memiliki suatu makna hanya dalam kaitannya dengan yang transendental. Bahkan Alqur’an penuh dengan ayat-ayat (atau tanda) yang menyatakan kesalinghubungan antara yang empiris dan transendental. Yang paling penting, wahyu menggarisbawahi pentingnya fakta bahwa yang empiris tidak memiliki makna ketika ia dipisahkan dari totalitasnya, seperti yang ingin diakui oleh ilmu Barat, melampaui batas-batas realitas empiris.
Dengan demikian, wahyu harus didekati bukan sebagai sejumlah pernyataan yang dapat diakses secara langsung, tetapi sebagai fenomena terberi yang terdiri dari tanda-tanda, dimana untuk memahaminya dibutuhkan interpretasi dan sistematiasasi yang konstan dan terus menerus. Bahkan Alqur’an menjelaskan dengan gamblang bahwa ia terdiri dari tanda (ayat) dimana pemahaman terhadapnya bergantung kepada proses pemikiran, kontemplasi dan penalaran.
Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi mereka yang mau berpikir (13:3) Sesungguhnya Kami jelaskan beberapa ayat kepada mereka yang mengetahui (6:97). Penelitian di atas menggarisbawahi fakta bahwa untuk memahami kebenaran wahyu, orang harus mendekatinya dengan cara yang sama dengan pendekatan terhadap fenomena-fenomena sosial atau bahkan fenomena alam. Alasannya, kebenaran seluruh fenomena itu tergantung pada kemampuan teori-teori yang dibangun oleh para sarjana dan ilmuan berdasarkan data yang berasal dari fenomena itu dalam menghasilkan penjelasan yang memuaskan terhadap realitas yang dialami.
Penempatan wahyu sebagai fenomena, dan oleh karenanya sebagai sumber pengetahuan dapat dibenarkan dengan mengutip alasan lain. Kualitas bukti yang digunakan untuk memahami realitas (yakni untuk menunjukkan secara objektif) yang dideskripsikan oleh teori-teori empiris, tidak memiliki mutu yang lebih tinggi dari bukti yang digunakan memahami realitas yang dideskripsikan oleh wahyu. Dalam kedua kasus tersebut, eksistensi fenomena yang dipahami secara bersamaan dilahirkan di dalam kesadaran berbagai individu yang memiliki kesempatan untuk mengalami elemen-elemen dasar fenomena dari dekat. Berarti, sebagaimana fenomena sosial atau fisik dapat dipahami oleh orang-orang yang telah mengalami berbagai elemen-elemen yang menyusunnya, maka wahyu Tuhan juga dapat dipahami oleh orang yang memiliki pengalaman tentang kebenaran berbagai tanda yang menyusunnya.
Dalam kedua kasus kebenaran tentang sesuatu yang diperoleh dengan serta merta, dipahami secara intuitif. Satu-satunya perbedaan bahwa realitas empiris yang dialami melalui indera dipahami melalui intuisi empiris, sementara realitas transendental yang dialami melalui wahyu dipahami melalui intuisi murni. Benar, bahwa ilmu Barat, dimulai dari Kant membatasi intuisi kesatuan elemen-elemen yang dipahami dari suatu fenomena kepada intuisi empiris, dengan menolak bahwa elemen transendental dapat dipahami. Tetapi Kant, seperti telah kita lihat sebelumnya, mampu mencapai reduksi ini dengan menciptakan kebingungan tentang proses intuisi murni. Meskipun sekilas Kant tampak secara benar memahami intuisi sebagai “seluruh representasi … dimana tidak ada sesuatu apapun yang tergolong sebagai sensasi”, namun dia menegaskan bahwa penggunaan intuisi murni mesti dibatasi pada realitas empiris. Tetapi jika intuisi murni dipahami sebagai suatu hasil abstraksi berturut-turut dari representasi yang beragam yang diperoleh melalui intuisi empiris, membawa pada suatu intuisi tunggal, dimana seluruh konsep disatukan. Penolakan Kant untuk mengakui realitas transendental yang dipahami dengan intuisi murni adalah sesuatu yang arbitrer dan dogmatik.
Di antara kontribusi Pendekatan Fenomenologis dalam Studi Islam Sebagaimana dinyatakan oleh Kuntowijoyo bahwa kita butuh ilmu sosial profetik, yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa. Yaitu ilmu sosial yang mampu mengubah fenomena berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Perubahan yang didasarkan pada tiga hal, yaitu cita-cita kemanusiaan, liberalisasi dan transendensi. Namun untuk mencapai perubahan tersebut, tidak bisa hanya mengandalkan fenomenologi saja, tetapi harus dibarengi dengan disiplin keilmuan lainnya. Misalnya antropologi. Melalui antropologi fenomenologis ini maka akan dapat dilihat hubungan antara agama dan negara. [6]
E. Contoh pendekatan fenomenologi
Para wali dan sunan dalam membentuk corak kebudayaan yang lama tidak dihilangkan dengan alasan agar masyarakat tidak terlalu kaget dengan perubahan. Dengan demikian, ajaran Islam dapat diterima dengan mudah dan tanpa ketakutan. Unsur-unsur tradisi masih melekat dapat dirasakan hingga sekarang, di antaranya acara tahlilan.
Tahlilan adalah acara doa bersama yang diadakan di rumah keluarga orang yang meninggal, yang diikuti oleh keluarga yang berduka, para tetangga, dan sanak-saudara orang yang meninggal. Tahlilan dimulai pada hari di mana orang bersangkutan meninggal, biasanya pada malam hari setelah salat magrib atau isya. Dalam pelaksanaannya, dibacakan ayat-ayat dari Al-Quran, terutama Surat Yaasin dari ayat pertama hingga terakhir, doa-doa agar sang almarhum atau almarhumah diampuni segala dosanya dan diterima amal-ibadahnya, serta salawat (salam) terhadap Nabi Muhammad beserta para kekuarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya.
Acara tahlilan ini lazimnya diselenggarakan selama tujuh hari berturut-turut. Setelah itu, diadakan pula tahlilan untuk memperingati 40 bahkan hingga 1.000 hari kematian almarhum/almarhumah. Peringatan 7, 40, dan 100 hari merupakan tradisi Indonesia pra-Islam, yakni budaya lokal yang telah bersatu dengan tradisi Hindu-Buddha. Pada zaman Majapahit, penghormatan terhadap orang yang meninggal dilakukan secara bertahap, yakni pada hari orang bersangkutan meninggal, 3 hari kemudian, 7 hari kemudian, 40 hari kemudian, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan 1000 hari kemudian. Terlihat bahwa acara tahlilan tak sepenuhnya ajaran murni Islam. Nabi Muhammad tak pernah mengadakan acara tahlilan bila ada yang meninggal, melainkan hanya mendoakan agar orang meninggal tersebut diampuni dosanya dan diterima keimanan Islamnya.[7]
BAB III
KESIMPULAN
Fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau segala sesuatu yang tampak atau yang menampakkan diri. Seorang Fenomenolog suka melihat gejala Fenomenolog bergerak di bidang yang pasti. Hal yang menampakkan dirinya dilukiskan tanpa meninggalkan bidang evidensi yang langsung. Fenomenologi adalah suatu metode pemikiran, “a way of looking at things”.
Dalam konteks studi agama, tujuan pendekatan fenomenologi tidak bermaksud untuk memperbandingkan agama-agama sebagai satuan-satuan besar, melainkan menarik fakta dan fenomena yang sama yang dijumpai dalam agama yang berlainan, mengumpulkan dan mempelajarinya per kelompok.
Ada beberapa langkah atau tahapan pendekatan fenomenologi dalam studi agama yang ditawarkan oleh Geradus Van der Leeuw dalam bukunya “Religion in essence and manifestation:A study in phenomenology of religion”:
1. Mengklasifikasikan fenomena keagamaam dalam kategorinya masing-masing
2. Melakukan interpolasi dalam kehidupan pribadi peneliti, dalam arti seorang peneliti dituntut untuk ikut membaur dan berpartisipasi dalam sebuah keberagamaan yang diteliti untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman dalam dirinya sendiri.
3. Melakukan “epochè” atau menunda penilaiandengan cara pandang yang netral.
4. Mencari hubungan struktural dari informasi yang dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang holistik
Diantara probematika pendekatan feomenologoi diantaranya Kesulitan pertama yang dihadapi dalam upaya membangun suatu pendekatan metodologis alternatif yang berakar pada ontologi Islami terletak pada penyingkiran wahyu Tuhan dari wilayah ilmu. Benar bahwa penyingkiran ini memiliki asal-usul dalam batasan tradisi ilmiah Barat sebagai akibat dari konflik internal antara ke agamaan Barat dengan komunitas ilmiah. Juga benar bahwa dalam tradisi Islam, wahyu dan ilmu tidak pernah dipahami sebagai dua hal yang eksklusif. Namun seorang sarjana muslim hampir tidak pernah dapat mengabaikan fakta bahwa wahyu ketuhanan berada di luar aktivitas ilmiah modern.
Sedangkan contoh dalam hal ini yaitu Para wali dan sunan dalam membentuk corak kebudayaan yang lama tidak dihilangkan dengan alasan agar masyarakat tidak terlalu kaget dengan perubahan. Dengan demikian, ajaran Islam dapat diterima dengan mudah dan tanpa ketakutan. Unsur-unsur tradisi masih melekat dapat dirasakan hingga sekarang, di antaranya acara tahlilan
DAFTAR PUSTAKA
Dikutip dari Rev. Emeka C. Ekeke & Chike Ekeopara, “Phenomenological Approach…,
Erricker , Clive, 2002. “Pendekatan Fenomenologis”, dalam Peter Connoly (Ed.), Aneka Pendekatan Studi Agama, Terj. Imam Khoiri, Cet. I. Yogyakarta: LKIS.
http://afriarengki.blogspot.co.id/2013/02/makalah-fenomenologi.html diakses 29 Oktober 2016
http://mazalahmakalah.blogspot.co.id/2016/03/pendekatan-fenomenologi-dalam-studi.html diakses 29 Oktober 2016
Nata, Abuddin. 2001. Metodologi Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Safi, Lousy. 2001, Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat Ancangan Metodologi Alternatif, Terj. Imam Khoiri, Jakarta: PT Tiara Wacana Yoga.
[2] Clive Erricker, “Pendekatan Fenomenologis”, dalam Peter Connoly (Ed.), Aneka Pendekatan Studi Agama, Terj. Imam Khoiri, Cet. I (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 110.
[3] Dikutip dari Rev. Emeka C. Ekeke & Chike Ekeopara, “Phenomenological Approach…, 271.
[4] Lousy Safi, Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat Ancangan Metodologi Alternatif, Terj. Imam Khoiri, (Jakarta: PT Tiara Wacana Yoga, 2001), hlm. 203.
[5] Ibid 210
[6] Abuddin Nata, Metodologi Islam , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 37
[7] http://mazalahmakalah.blogspot.co.id/2016/03/pendekatan-fenomenologi-dalam-studi.html diakses 29 Oktober 2016
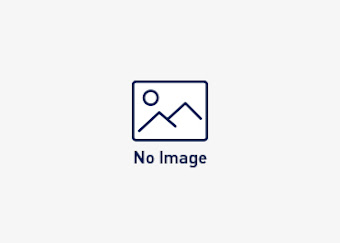



Social Media